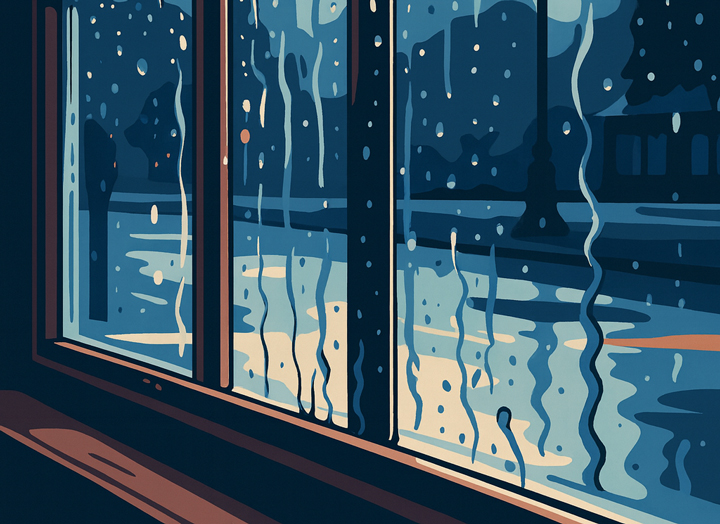
Hujan mengguyur kota dengan derasnya, membasahi kaca jendela kamarku. Rintiknya jatuh berirama, seolah menulis kisah sendiri di balik kabut sore yang muram. Di luar, petir sesekali menyambar, menggelegar bersahutan dengan deru angin. Namun anehnya, di dalam kamar, aku justru merasa tenang.
Kopi hangat di meja kecil mengepul pelan, sementara aku bersandar di tepi ranjang, membuka novel berjudul “Garis Takdir Si Anak Tunggal.” Aku tersenyum kecil. Judulnya terasa akrab. Mungkin karena aku sendiri adalah anak tunggal. Tidak pernah tahu rasanya memiliki saudara kandung, tidak pernah merasakan berebut mainan, berdebat tentang hal sepele, atau diam-diam saling menyimpan rahasia kecil di balik pintu kamar.
Orang tuaku selalu menanamkan kemandirian sejak aku kecil. “Kamu harus bisa berdiri di atas kaki sendiri,” kata Ayah suatu pagi, ketika aku berusia sepuluh tahun dan baru saja belajar menanak nasi. Saat teman-temanku masih dimanja, aku sudah belajar mencuci pakaian sendiri, membersihkan rumah, bahkan menemani Ibu memasak. Aku tidak pernah merasa terbebani. Justru ada kebanggaan tersendiri setiap kali mereka memuji hasil kerjaku.
Namun, malam-malam panjang sering menghadirkan kesepian yang diam-diam menyelinap. Saat teman-temanku bercerita tentang pertengkaran lucu dengan kakaknya, atau tawa hangat bersama adiknya, aku hanya bisa tersenyum. Ada ruang kosong di dalam dada yang tak tahu bagaimana mengisinya. Kadang aku bertanya dalam hati, apakah aku kurang bahagia karena tak punya saudara?
Tahun demi tahun berlalu. Aku tumbuh menjadi remaja yang mandiri, aktif mengikuti berbagai lomba, berkenalan dengan banyak orang, dan menulis di mana pun aku berada. Di kafe, taman, atau ruang tunggu stasiun. Dari orang-orang itulah aku belajar bahwa setiap pertemuan bisa menciptakan “keluarga kecil” baru. Mereka yang tertawa bersama saat aku menang lomba. Mereka yang diam-diam menghibur ketika aku kalah. Dari mereka, aku belajar arti berbagi dan pentingnya dukungan dalam hidup.
Beberapa halaman novel kubaca, tapi pikiranku justru melayang ke masa lalu. Tentang seseorang yang pernah membuatku merasa tidak sendirian. Tentang dia yang dulu menulis pesan manis di pagi hari dan menelponku sebelum tidur. Tentang kebersamaan yang kukira akan bertahan lama.
Namun sore itu, hujan turun tanpa jeda, seolah langit ikut menumpahkan perasaanku yang kacau. Aku duduk di taman kampus Seribu Janji, tempat di mana dulu kami sering bertemu, aku dan dia. Kini, hanya ada bangku kosong, basah oleh air hujan yang menetes dari dahan mangga di atasnya.
Sudah tiga hari aku tahu segalanya. Tentang dia. Tentang perempuan lain yang tiba-tiba muncul di foto unggahannya. Tentang pesan singkat yang menjelaskan segalanya dalam kalimat dingin.
“Maaf, Ainun. Aku nggak bisa terusin hubungan ini. Aku udah sama orang lain.”
Awalnya aku marah, lalu hancur, lalu diam. Diam yang membekukan dada.
“Hujan-hujanan sendiri? Kamu mau sakit?” Suara itu memecah lamunanku. Vivi datang dengan payung birunya, napasnya terengah karena berlari. Ia duduk di sampingku, tanpa bicara apa-apa lagi.
“Aku bodoh, Vi,” suaraku serak. “Aku pikir dia bakal jadi orang yang bisa aku percaya.”
Vivi menatapku lama. “Percaya itu nggak salah, Ainun. Tapi kadang, orang yang kita percayai justru jadi pelajaran yang paling besar.”
Aku menghela napas panjang. “Aku capek. Semua rasanya sia-sia. Aku udah berusaha jadi yang terbaik, tapi ternyata… nggak cukup.” Air mataku akhirnya jatuh, bercampur dengan air hujan yang membasahi pipi.
Vivi memiringkan payungnya ke arahku, lalu berkata lembut, “Ainun, denger ya. Kamu nggak harus kuat terus. Kadang, patah itu juga bagian dari bertahan. Kamu boleh sedih, kamu boleh marah. Tapi jangan biarin luka ini bikin kamu lupa. Kamu masih punya orang-orang yang sayang sama kamu.”
Aku terdiam. Hanya suara hujan yang mengisi sela napas kami.
“Orang tuamu, temanmu, bahkan aku,” lanjut Vivi dengan nada pelan, “kami mungkin nggak bisa gantiin rasa cinta yang hilang, tapi kami bisa jagain kamu supaya nggak tenggelam di dalamnya.”
Kata-katanya terasa seperti selimut hangat di tengah badai. Aku menatapnya, mataku buram oleh air dan tangis. Vivi tersenyum samar. “Keluarga itu nggak selalu tentang siapa yang punya hubungan darah, Ainun. Kadang, keluarga adalah orang yang tetap tinggal, waktu semua orang memilih pergi.”
Aku menunduk, menatap tanah yang basah. Entah kenapa, di tengah hujan dan luka yang belum kering, aku merasa sedikit lega.
Malam itu aku pulang dengan perasaan yang berbeda. Aku memandangi foto keluarga di meja belajar. Ayah tersenyum kaku, Ibu tertawa lebar, dan aku di tengah mereka. Entah kenapa, foto itu tampak lebih hidup dari biasanya. Aku baru benar-benar memahami bahwa keluarga bukan hanya mereka yang lahir dari rahim yang sama, tapi juga mereka yang membuat kita merasa “pulang.”
Sudah masuk tahun ketiga aku tinggal di Malang. Kota ini mulai akrab di mataku, tapi kadang masih terasa asing di hati. Setiap pagi aku berangkat kuliah ke UIN Malang, menembus udara dingin yang khas. Ada banyak hal yang sudah berubah dalam hidupku, tapi rasa sepi itu, entah kenapa, masih sesekali mampir diam-diam.
Kamar kosku kecil, tapi cukup nyaman. Ada meja belajar yang penuh buku catatan, dinding dengan foto keluarga yang kupajang di dekat jendela, dan secangkir kopi yang selalu menemani malam-malam panjangku. Dari jendela itu, aku bisa melihat lampu-lampu kota yang berpendar lembut, seperti bintang-bintang yang turun ke bumi. Tapi tetap saja, ada saat di mana semuanya terasa sunyi.
Kadang aku merindukan hal sederhana, suara Ibu memanggilku makan, teguran Ayah karena bangun kesiangan, atau sekadar tawa hangat di ruang tamu. Rasa rindu itu tidak pernah benar-benar hilang, hanya berubah bentuk. Kini, ia menjadi tenaga yang mendorongku untuk terus belajar dan bertahan.
Selain kuliah, aku mengisi waktu dengan mengajar ngaji secara online. Awalnya hanya satu anak, namanya Alvaro. Dia kelas 1 SMP. Tapi kini sudah ada tiga orang dari berbagai kota. Setiap sore dan malam, aku menyalakan laptop, membuka aplikasi pertemuan daring, dan menyapa wajah-wajah mereka yang muncul di layar.
Di sela kesibukan kuliah dan tugas-tugas yang menumpuk, les ngaji online itu seperti jeda hangat di tengah lelah. Setiap kali mereka tersenyum, rasanya jarak antara Malang dan rumah tak lagi sejauh itu. Ada rasa “pulang” yang perlahan tumbuh dari setiap salam, setiap tawa kecil, dan setiap ucapan “terima kasih, Kak Ainun.”
Malamnya, hujan turun lagi. Aku duduk di tepi jendela kos, menatap butir air yang berlari di kaca. Kali ini, hujan tak lagi terasa dingin. Ia justru membawa ketenangan seperti tangan lembut Ibu yang menepuk bahuku dulu setiap kali aku gelisah.
Aku tersenyum kecil. Dua tahun di Malang mengajarkanku banyak hal tentang kemandirian, tentang kesabaran, dan terutama tentang arti keluarga yang sebenarnya. Keluarga bukan sekadar mereka yang tinggal serumah, tapi juga mereka yang hadir di hati, meski hanya lewat layar kecil dan jarak ribuan kilometer.
Kini aku tahu, aku tidak pernah benar-benar sendiri. Karena di antara suara hujan dan cahaya redup kota Malang, selalu ada doa, kasih, dan perhatian yang menjelma menjadi rumah tempat aku selalu bisa kembali, meski tanpa harus pulang.

Tinggalkan Balasan