Penulis: Nurul Fatta*
Beberapa hari lalu, seorang teman mengirim
pesan pendek, menanyakan lowongan kerja, Mas Dani namanya. Sekaligus memberi
kabar bahwa ia termasuk tenaga non-ASN yang dirumahkan Pemkab Situbondo. Ia
bilang, “tak apalah, Mas. Mungkin nanti ada pekerjaan lain.” Saya membaca
pesannya dengan rasa campur aduk—antara sedih, prihatin, sekaligus hormat atas
sikap legawanya.
Namun, tidak semua merespon hal ini dengan
tenang seperti Mas Dani. Tepat tanggal 3 Mei, saya membaca tulisan seorang
kawan lain asal Situbondo yang suaranya jauh berbeda. Nada tulisannya keras,
dimuat salah satu media yang bernaung di Jogja. Ia mengkritik solusi yang
ditawarkan Bupati Situbondo soal pemutusan tenaga non-ASN, yaitu sistem
outsourcing, dan bantuan modal usaha sebagai solusi yang rapuh, kasarnya
asal-asalan lah. Kritiknya personal, dan jujur saja—sedikit terburu-buru.
Saya tidak hendak membela siapa pun. Tapi
izinkan saya menawarkan cara pandang lain atau meluruskan peta persoalan agar
kritik kita tidak tersesat di jalan dan tetap relevan dengan konteks yang
sebenarnya.
Saya memahami kekecewaan kawan saya itu. Tapi
sayangnya, sebagian kritik yang ia lontarkan terasa terlalu personal. Ia
menuduh bahwa pelatihan inkubator bisnis yang digagas oleh Bupati
Situbondo—sebut saja Mas Rio—sebelum menjabat hanyalah pencitraan, dan
materinya bisa ditemukan di internet.
Kritik seperti ini tentu sah-sah saja. Tapi
pendekatan yang terlalu fokus pada sosok alih-alih subtansi kebijakan, justru
berisiko melemahkan pesan itu sendiri. Ketika program langsung disimpulkan tak
berguna hanya karena digagas oleh figur tertentu, kita menjadi abai pada
kesempatan untuk menilai dampaknya secara objektif. Lebih dari itu, cara
seperti ini bisa menutup ruang diskusi yang sehat, padahal kritik yang tajam
justru lahir dari pembacaan yang adil terhadap konteks.
Sebelumnya, Pemkab Situbondo terpaksa
merumahkan sekitar 600 tenaga non-ASN, dan langkah ini langsung memantik
berbagai respon. Padahal, pemutusan hubungan kerja non-ASN bukan hanya terjadi
di Situbondo. Kabupaten tetangga seperti Jember dan Lumajang pun mengalami hal
yang sama. Jadi bukan soal ‘hanya di Situbondo’. Pertanyaannya justru lebih
mendasar, kenapa mereka harus dirumahkan?
Mari kita lihat kerangka aturannya, sebab,
penting untuk dipahami bahwa keputusan pemerintah daerah merumahkan tenaga
non-ASN bukanlah langkah sepihak, apalagi semata-mata kehendak bupati. Ada
dasar hukum yang jelas. Sejak UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan PP Nomor
49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK diberlakukan, negara hanya mengakui dua
jenis pegawai di lingkungan instansi pemerintah, apa itu? ASN dan PPPK. Di luar
itu, khususnya tenaga honorer, tak lagi memiliki payung hukum. Bahkan jika
seorang bupati ingin mempertahankan mereka, ia justru berisiko melanggar aturan
dengan sanksi yang berlaku.
Karena itu, seluruh tenaga non-ASN wajib
didata ke BKN sebelum Oktober 2022, dengan sejumlah syarat ketat, seperti harus
masih aktif bekerja, diangkat minimal oleh pimpinan unit, dibayar atau digaji dari APBN /APBD, dan sudah bekerja
minimal satu tahun per akhir 2021.
Bagi yang memenuhi syarat, dapat mengikuti
seleksi PPPK. Di Situbondo sendiri, seleksi PPK berlangsung dalam dua gelombang
yaitu 5-8 Desember 2024 dan 7-10 Mei 2025. Mereka yang lulus akan diangkat
sebagai ASN berstatus PPPK. Tapi bagi yang tidak terdata atau tidak ikut
seleksi, tak ada lagi ruang hukum untuk dipekerjakan.
Jika aturan ini sudah berlaku, mestinya memang
tak ada lagi pengangkatan honorer sejak batas akhir pendataan non-ASN ke dalam
database BKN pada bulan Oktober tahun 2022, atau sejak berlakunya PP 49/2018
yang jatuh pada tanggal 28 September 2023 yang mewajibkan kepegawaian hanya
terdiri dari dua jenis, yaitu ASN dan PPPK.
Tapi tak semua daerah langsung patuh, termasuk pemerintah
Situbondo—entah karena tekanan kebutuhan birokrasi atau peninggalan
“kesewenang-wenangan” pemimpin sebelumnya. Dan kini, konsekuensinya harus
dihadapi oleh kepemimpinan pemerintah Situbondo yang baru.
Lalu muncul kritik dari tulisan kawan saya
tadi, kira-kira begini, kenapa solusinya harus outsourcing? Bukankah lebih
manusiawi kalau tetap honorer?
Saya justru bertanya-tanya, apakah logika ini
tidak terbalik? Dalam tulisan kawan saya itu, gaji honorer dianggap lebih
pasti, struktur pekerjaan lebih jelas. Tapi bukankah selama ini justru banyak
honorer yang menerima gaji tidak jelas, di bawah UMK, tanpa kepastian waktu
bahkan berbulan-bulan tidak digaji, itupun tanpa perlindungan hukum. Sehingga
reformasi birokrasi hadir bersama UU ASN dan PP 49 2018 beserta turunannya itu,
tujuannya untuk menyelesaikan praktik non-ASN yang menyimpan banyak masalah
tersebut.
Mereka kadang bertahan bukan karena sistemnya
baik, tapi karena tidak ada pilihan lain. Kadang perekrutan pun sering tidak
berbasis kompetensi, melainkan karena kedekatan dengan elite politik, tim
pendukung kepala daerah terpilih atau “kenal sana-sini.” Ini bukan sistem yang
sehat. Pemerintah mencoba keluar dari ini lewat outsourcing—yang meskipun bukan
solusi ideal, setidaknya menjamin gaji dan struktur kerja yang lebih jelas.
Kemudian soal bantuan modal usaha Pemkab
Situbondo. Apakah berwirausaha solusi terbaik bagi semua? Tidak juga. Tapi
mengapa langsung ditolak sebelum dicoba? Memang tak semua orang cocok
berwirausaha, tapi tak berarti semuanya gagal. Shifting mindset memang tidak
mudah jika sejak awal sudah pesimis, dan apalagi percaya bahwa satu-satunya
jalan hidup layak adalah jadi ASN. Padahal, hari ini, Pemerintah Situbondo
mengusung semangat “naik kelas”, yang justru mengajak kita untuk
keluar dari pola pikir lama seperti itu.
Kita tidak sedang bicara soal pekerjaan
semata. Kita sedang bicara tentang mindset. Tentang keberanian mengambil
risiko. Tentang usaha untuk tidak menggantungkan seluruh masa depan pada
selembar surat pengangkatan.
Selama ini, pemerintah dianggap sebagai
penyedia kerja utama. Seolah-olah seluruh beban hidup harus ditanggung negara.
Padahal, dalam relasi sosial modern, hubungan antara pemerintah dan warga sipil
bersifat legal—bukan paternalistik. Pemerintah membuka akses dan menciptakan
ekosistem. Tapi warga juga harus berjalan sendiri.
Mendorong masyarakat untuk berwirausaha bukan
berarti lepas tangan. Justru itu bagian dari upaya membangun jaringan sosial
dan ekonomi yang lebih dinamis. Semakin banyak warga membuka usaha, semakin
besar peluang tumbuhnya pasar, dan dengan sendirinya, investasi akan ikut
datang. Di sinilah pentingnya kolaborasi antara negara, warga dan sektor
swasta.
Apakah semua ini mudah? Tentu tidak. Tapi
kalau kita terus menerus menolak semua perubahan karena takut gagal, kapan kita
akan bergerak? Bukankah hidup ini memang rangkaian dari jatuh dan bangkit?
Kadang gagal usaha, kadang gagal daftar CPNS. Tapi bukankah kita manusia, bukan
mesin yang hanya kenal satu jalan?
Saya tidak sedang membela pemerintah
sepenuhnya. Kritik tetap penting. Tapi mari arahkan kritik kita pada struktur
kebijakan, bukan sekadar pada figur pemimpin. Kita bisa tidak sepakat, tapi
tetap menjaga cara berpendapat. Sebab tantangan terbesar kita hari ini bukan
hanya soal status kerja, tapi bagaimana kita bersama-sama naik kelas—secara
ekonomi, mentalitas, dan keberanian mengambil peluang baru.
Saya percaya, kritik itu penting. Tapi yang
lebih penting lagi, bagaimana menjadikannya sebagai sumbu perubahan, bukan
sekadar pelampiasan.
__
Penulis merupakan konsultan politik nasional. Asli Situbondo, tinggal sementara di Jakarta.
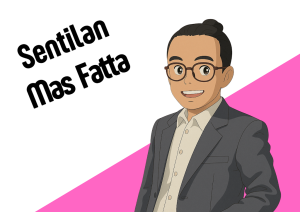

Tinggalkan Balasan